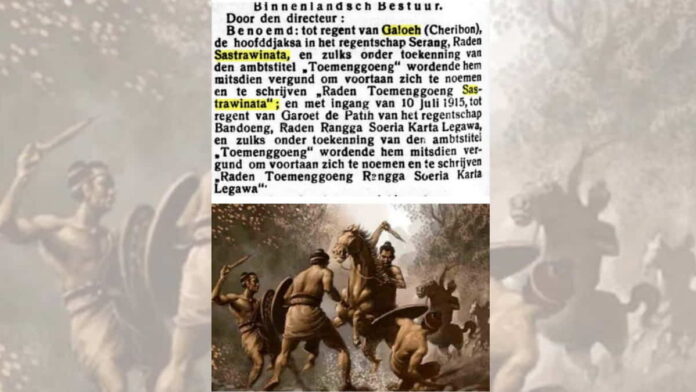Raden Tumenggung Sastrawinata atau dikenal juga dengan nama Raden Adipati Aria (RAA) Sastrawinata adalah tokoh di balik pergantian nama Kabupaten Galuh jadi Ciamis.
Akhir-akhir ini isu mengenai pengembalian nama Galuh untuk kabupaten Ciamis ramai kembali. Ada beberapa alasan kenapa sehingga sebagian masyarakat Ciamis ingin mengembalikan nama daerahnya menjadi Galuh.
Menurut berbagai literatur yang ada, perubahan nama kabupaten Galuh menjadi Ciamis ini digagas oleh bupati Ciamis zaman kolonial Belanda bernama Raden Tumenggung Sastrawinata.
Perubahan nama Galuh menjadi Ciamis merupakan upaya bupati Sastrawinata dalam mengubah politik identitas Pasundan yang terlalu kuat di daerah tersebut.
Baca Juga: Bupati Ciamis RAA Sastrawinata: Dihormati Belanda, Dibenci Rakyat
Terlepas dari alasan di atas, perubahan nama Galuh menjadi Ciamis yang dilakukan oleh Sastrawinata konon akibat kecemburuan bupati pro-kolonial Belanda tersebut, lantaran ia bukan keturunan Kerajaan Galuh.
Menurut koran berbahasa Belanda, De Sumatera Post tanggal 03 Agustus 1915, Raden Tumenggung Sastrawinata adalah bupati Ciamis pertama kali yang bukan merupakan keturunan Raja Galuh, Ia keturunan ningrat yang berprofesi menjadi Jaksa di Serang, Banten.
Pergantian nama Galuh menjadi Ciamis yang dilakukan oleh Sastrawinata kemudian menjadi kontroversial. Ada yang menganggap nama Ciamis adalah nama cemoohan orang Jawa untuk rakyat Galuh yang berarti Bau (Amis: Anyir).
Dari peristiwa kontroversial ini, penulis ingin membahas tentang sejarah perubahan nama Galuh menjadi Ciamis. Adapun artikel ini bermaksud untuk menjelaskan apa saja penyebab pergantian nama Galuh-Ciamis oleh bupati Sastrawinata sejak tahun 1914-1935.
Alasan Raden Tumenggung Sastrawinata Ganti Galuh Jadi Ciamis
Nama Ciamis lahir akibat Raden Tumenggung Sastrawinata mengganti nama Galuh menjadi Ciamis. Pergantian nama ia lakukan sejak periode pertama masa jabatannya sebagai bupati pada tahun 1914-1935.
Adapun penyebab nama Galuh berganti menjadi Ciamis karena garis keturunan sang bupati yang berbeda dengan pendahulunya.
Sastrawinata berasal dari ningrat Banten, jabatannya yang berprestasi sebagai Jaksa kolonial di Serang, Banten membuat dirinya dipindah tugaskan menjadi Bupati untuk wilayah Priangan, khususnya di daerah Galuh.
Artinya Sastrawinata yang berasal dari pegawai pemerintah Hindia Belanda ini tidak punya garis keturunan Galuh, (bukan orang Galuh asli). Sementara waktu itu karakter Sastrawinata sedikit berbeda dengan para pendahulunya.
Ia merupakan satu-satunya bupati di Galuh yang berani mengganti nama daerah tersebut dengan Ciamis karena ingin menciptakan keberagaman dalam kehidupan dua suku yang pernah bertentangan (Sunda-Jawa).
Terutama ketika masyarakat Galuh sebagai etnis Sunda menolak dominasi Jawa (Mataram) yang telah masuk menguasai daerah tersebut sejak tahun 1595.
Keberanian Sastrawinata mengganti nama Galuh menjadi Ciamis ini berawal saat pemerintah kolonial dan pejabat Mataram memberikan gelar Toemenggoeng (Tumenggung).
Artinya, suatu gelar kehormatan untuk tokoh, pemimpin yang diyakini oleh kerajaan mampu berkarya serta melestarikan budaya dan menjaga keberagaman, serta menciptakan persatuan.
Awalnya bertujuan baik, yaitu ingin menetralkan hubungan Sunda dan Jawa pasca kekalahan Bala Sentana Kerajaan Sunda dari Angkatan Perang Majapahit, hingga penguasaan Galuh oleh Mataram pada abad ke-16 masehi.
Namun di sela-sela tujuan baik itu ada kepentingan terselubung antara Sastrawinata dengan pemerintah kolonial Belanda. Rupanya mereka sama-sama ingin menghilangkan sejarah Adiluhung kerajaan Galuh yang kuat dan kerap menentang Belanda.
Baca Juga: Sejarah Pemberontakan PKI 1926, Pelakunya Digantung di Alun-alun Ciamis
Akhirnya bupati Sastrawinata mengubah nama Kabupaten Galuh menjadi Ciamis. Menurutnya nama ini tepat untuk menggambarkan daerah ex-Kerajaan Galuh yang berarti daerah penuh dengan kesejahteraan dan kesuburan.
Kontroversial Nama Ciamis
Sebagian pendapat tidak menyetujui arti nama Ciamis sebagaimana yang diusulkan oleh bupati Sastrawinata yaitu, daerah yang penuh dengan kesejahteraan dan kesuburan.
Mereka lebih percaya nama Ciamis berasal dari sebuah kata cemoohan orang Jawa (Mataram) terhadap masyarakat Sunda Galuh yang berarti Bau Amis: Anyir.
Pernyataan ini merujuk pada peristiwa Perang Bubat yang pernah terjadi tahun 1357. Perang tersebut melibatkan masyarakat Sunda yang menyerang Majapahit namun mengalami kekalahan.
Banjir darah pun terjadi di pihak para Sentana Kerajaan Sunda yang mengakibatkan bau Amis: Anyir dalam bahasa Jawa.
Kekalahan dalam Perang Bubat ini kemudian diadopsi menjadi cemoohan oleh orang Jawa (Mataram) seiring dengan penguasaan daerah Galuh oleh mereka sejak tahun 1595.
Orang-orang Jawa menyebut sebagian bekas daerah kekuasaan kerajaan Galuh dengan sebutan Ci yang berarti Air, dan Amis atau Anyir. Kalau digabungkan menjadi Air yang Bau Amis. Mungkin toponimi ini diambil dari peristiwa “Banjir Darah” tadi akibat Perang Bubat.
Peristiwa ini yang kemudian membuat sebagian orang Galuh tidak terima daerahnya berganti nama menjadi Ciamis. Apalagi penamaan ini mendorong terjadinya eksodus besar-besaran orang Jawa ke wilayah kekuasaan Galuh yang menimbulkan akulturasi budaya Jawa-Sunda.
Hingga hari ini bisa kita lihat hasil akulturasi budaya Jawa-Sunda ini ada di beberapa titik kekuasaan Galuh dahulu. Antara lain di daerah Majenang, Lakbok, Banjar, dan sekitarnya.
Ciamis Bukan Berarti Bau Anyir
Masyarakat Ciamis saat ini ingin nama Galuh kembali muncul menjadi nama kabupaten mereka. Sebab nama Galuh sangat mewakili masyarakat Sunda berarti “Permata yang Baik”.
Namun terlepas dari kontroversial pengertian nama Ciamis yang berarti bau anyir dalam bahasa Jawa ini, dampaknya bisa membuat rancu dan bisa mengakibatkan kesesatan sejarah.
Sebab jika kita mengacu pada toponimi Amis yang berarti anyir dalam bahasa Jawa besar kemungkinan salah pengertian. Karena kata Amis berdiri sendiri dari bahasa Indonesia non-resapan bahasa Jawa, dan pemakaiannya umum.
Kecuali jika kita melihat pengertian Ciamis ini sebagai toponimi yang berarti daerah yang sejahtera dan subur sebagaimana yang dimaksud Sastrawinata di awal.
Meskipun ada intrik politik dalam tujuan perubahan nama Galuh ke Ciamis, namun pengertian dari Ciamis itu sendiri tidak melibatkan cemoohan yang berarti Bau Anyir.
Baca Juga: Wabah Pes di Ciamis Tahun 1911 yang Membuat Kolonial Kelimpungan
Sastrawinata, Bupati yang Dekat dengan Kolonial Belanda
Kedekatan Sastrawinata sebagai bupati yang berani mengganti nama Galuh menjadi Ciamis ini telah memberikan simbol adanya intrik politik. Tujuannya untuk memecah belah Galuh daerah dominasi Sunda yang kerap menentang Belanda.
Dengan diubahnya nama Galuh menjadi Ciamis, bupati Sastrawinata telah menjalankan tugas dari pemerintah kolonial untuk mengunggulkan etnis Mataram di Tatar Sunda.
Semua ini dilakukan untuk mengadu domba dua Suku yang saat itu punya masa lalu buruk. Dengan demikian mereka bisa saling bersinggungan satu sama lain yang berakhir pada keuntungan bagi pemerintah kolonial Belanda.
Tujuan lain dari mengunggulkan suku Jawa di Ciamis juga merupakan tujuan kedua pemerintah kolonial Belanda yang menginginkan devide et impera (politik adu domba) ini terjadi.
Sebab tujuan awal dari dominasi Suku Jawa (Mataram) di Galuh yaitu untuk menciptakan ketenangan berpolitik Belanda yang licik. Sebab kala itu Mataram diduduki oleh pejabat-pejabat yang dekat dengan Belanda, dan sudah terbiasa melakukan interaksi yang nyaman.
Belanda juga menganggap Mataram adalah kerajaan besar yang hingga abad ke-20 masih berjaya dan bisa diajak kerjasama.
Bupati Sastrawinata dekat dengan pemerintah kolonial dan kerajaan Mataram. Bahkan diberikan gelar Toemenggoeng yang berarti penghormatan mutlak untuk pemimpin Ciamis kala itu.
Jadi Sasaran Amuk PKI
Hal inilah yang kemudian membuat masyarakat Ciamis memberontak. Pemberontakan tersebut juga ditunggangi oleh PKI yang dipimpin tiga tokoh komunis Ciamis, yaitu Egom, Dirdja, dan Hasan pada tahun 1926.
Pemberontakan ini bertujuan untuk menghancurkan kekuasaan Sastrawinata. Bahkan ada yang mengatakan jika pemberontakan PKI di Ciamis tahun 1926 ini berupaya untuk menculik dan membunuh Bupati Sastrawinata.
Baca Juga: Pemberontakan PKI di Ciamis 1926, 130 Orang Mengungsi ke Tjigoegoer
Namun tujuan tersebut gagal. Masyarakat Ciamis yang berafiliasi dalam pemberontakan tersebut ditangkap. Sementara para pemimpin pemberontakan dikenakan hukuman gantung oleh pemerintah kolonial melalui keputusan bupati Sastrawinata di depan alun-alun Ciamis.
Karena pemberontakan PKI di Ciamis gagal, kejayaan bupati Sastrawinata yang pro-kolonial Belanda ini terhitung langgeng.
Menurut surat kabar Belanda Bataviaasch Nieuwsblad, tanggal 03 Juli 1915, Sastrawinata menjabat menjadi bupati Ciamis tiga kali berturut-turut. Terhitung sejak tahun 1914 sampai dengan 1935, Sastrawinata menjabat sebagai bupati Ciamis yang penuh kontroversi. (Erik/R7/HR-Online/Editor-Ndu)